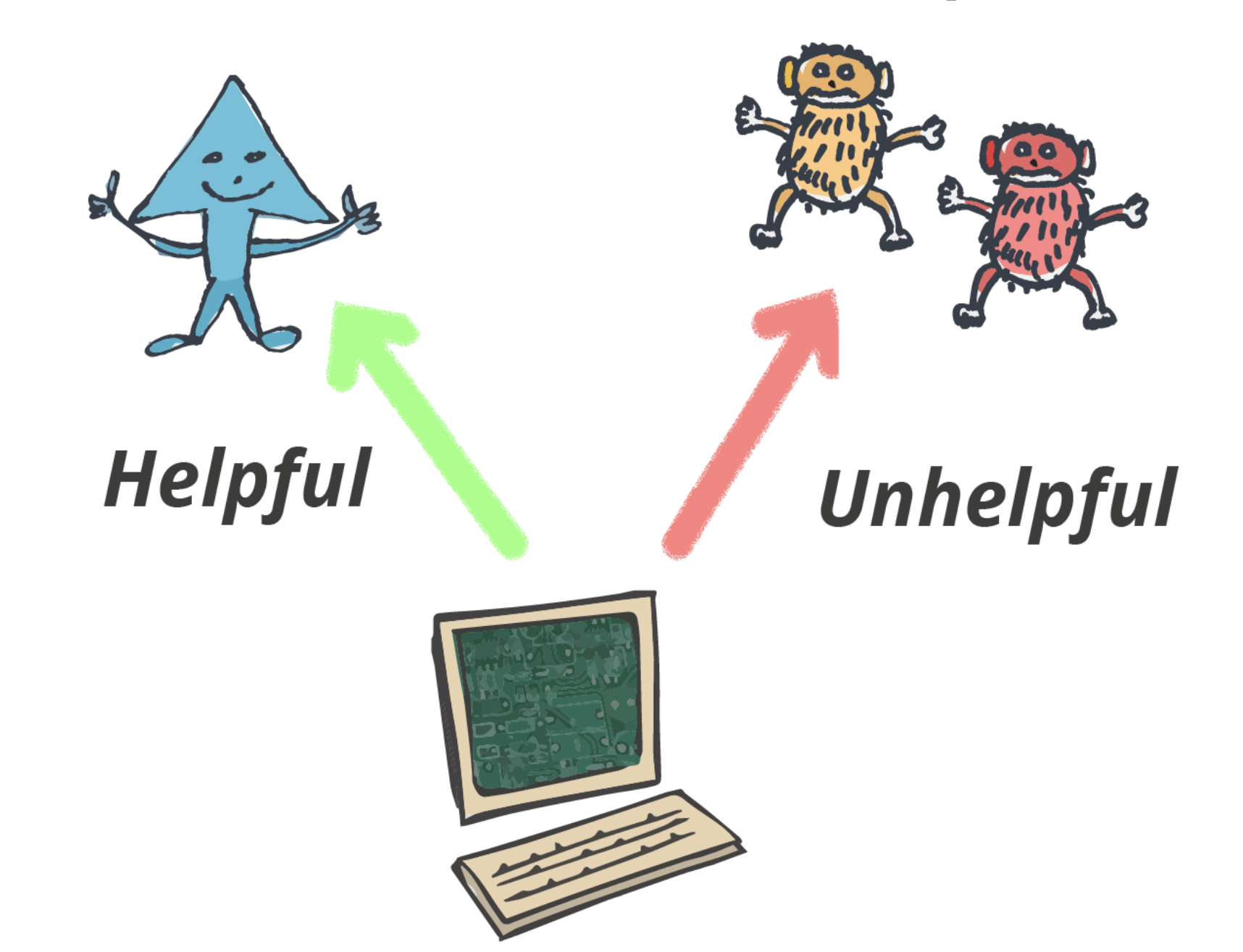Dunia musik kembali berkabung ketika mendengar kabar berpulangnya Eddie Van Halen, pada usia 65 tahun. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober kemarin setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker tenggorokan yang menggerogoti.
Berita ini tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi para musisi dan penggemar di seluruh dunia. Di lain pihak, angka penjualan album band Van Halen meningkat hingga 6198% sejak kematian Eddie. Orang beramai-ramai ingin mengenang karyanya yang apik. Bagaimana tidak, seorang diri ia bertanggung jawab atas lahirnya generasi gitaris sehingga banyak yang ingin menjadi Eddie Van Halen berikutnya. Dengan gaya bermain yang sangat unik sekaligus mencengangkan, tak terbilang gitaris yang meniru teknik tapping khas Eddie, namun tak ada satu pun yang bisa menangkap esensi dan keindahan permainan sang maestro.
Eddie Van Halen sendiri mencapai ketenaran dan kesuksesan lewat band yang ia dirikan bersama dengan kakaknya Alex, yaitu Van Halen. Formasi pertama yang beranggotakan dirinya, Alex, David Lee Roth, dan Michael Anthony merilis enam album sejak tahun 1978, serta melahirkan lagu-lagu hits seperti “Jump”, “You Really Got Me”, dan “Dance the Night Away”. Hilangnya vokalis David Lee Roth yang digantikan oleh Sammy Hagar tidak berpengaruh pada popularitas mereka, yang masih merilis lagu-lagu seperti “When It’s Love” dan “Dreams”.
Di balik ketenarannya, Eddie Van Halen dan kakaknya melalui masa kanak-kanak yang cukup menakutkan. Ayahnya, Jan Van Halen adalah seorang berkebangsaan Belanda, sedangkan ibunya Eugenia berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, Eddie dan kakaknya sering menjadi korban rasisme sejak pindah ke Amerika Serikat. Mereka dianggap sebagai masyarakat “kelas dua”, sehingga sering dilecehkan oleh teman-teman mereka sejak kecil.
“Mereka (Eddie dan Alex) tumbuh di lingkungan rasis yang memaksa mereka untuk meninggalkan negara mereka. Mereka datang ke Amerika Serikat dan tidak dapat menggunakan bahasa Inggris di awal tahun 1960an,” ujar mantan vokalis Van Halen, David Lee Roth dalam sebuah wawancara.
Eddie dan Alex sendiri sudah menjadi korban rasisme sejak mereka tinggal di Belanda. Sebagai keturunan setengah Indonesia, mereka sering dianggap sebagai kasta yang lebih rendah.
“Kami sudah sering melewati fase tersebut (korban rasisme) di Belanda, sejak kelas satu SD. Sekarang, ketika kami pindah ke negara yang baru dan tidak menguasai bahasanya serta tidak mengenal apapun, hal tersebut menjadi semakin menyeramkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi saya pikir hal tersebut yang membuat kami semakin kuat karena kondisi tersebut memaksa kami untuk menjadi demikian. Di Amerika, orang berkulit putihlah yang sering mengerjai kami dengan merobek pekerjaan rumah dan buku-buku kami, membuat kami menelan pasir, dan sebagainya. Anak-anak berkulit hitamlah yang membela kami,” ujar Eddie Van Halen pada wawancara yang dilakukannya tahun 2017 silam.
Kenyataan tersebut tidak menghentikannya menjadi seorang bintang dan panutan bagi miliaran orang. Karya-karyanya serta pengalamannya menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang tidak bisa diukur dari ras atau keturunan, tetapi melalui usaha dan kerja keras. Eddie Van Halen tidak lagi dipandang sebagai minoritas, namun sebagai idola dan bintang.
Image Source: Rollingstone.com