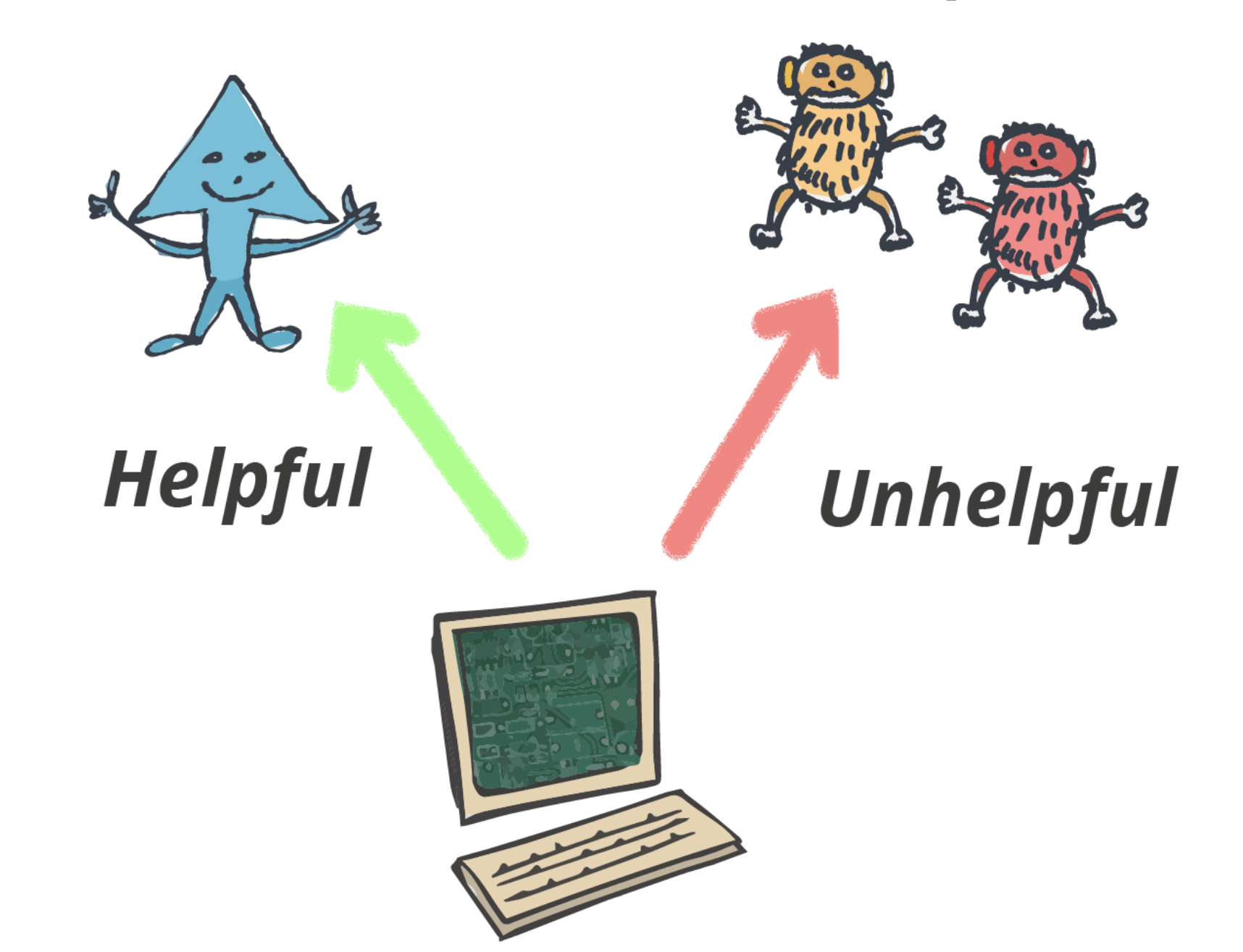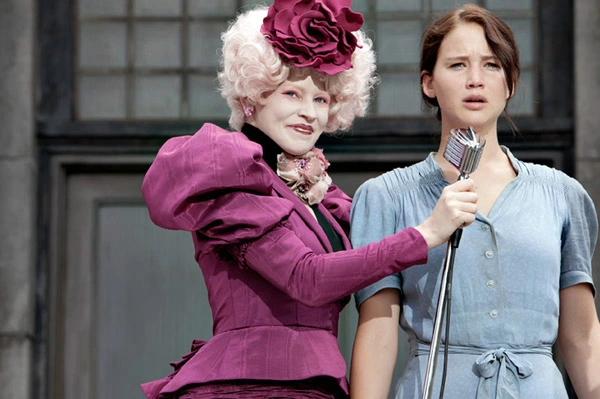Budaya pembatalan, yang juga dikenal sebagai cancel culture, semakin merambah ke dalam era digital saat ini. Peran media sosial dalam fenomena ini sangat signifikan, karena platform-platform ini memfasilitasi orang untuk menyuarakan pendapat dan kritik. Melalui media sosial, masyarakat semakin familiar dengan konsep dan praktik cancel culture.
Berbagai figur publik atau brand yang melakukan tindakan yang mengecewakan atau dianggap tidak sesuai sering kali menjadi sasaran dari cancel culture. Di Indonesia, fenomena ini masih umumnya terjadi dalam skala kecil dan sering dipandang sebagai hal yang lebih sering muncul di wilayah perkotaan.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Clark (2020) mengungkapkan cancel culture adalah fenomena yang secara unik diciptakan oleh dua sisi, yaitu permintaan kapitalis, yakni media massa, sekaligus dari sisi audiens yang terhubung kepada media sosial. Sebelumnya, Bromwich (2018) dalam tulisannya berjudul “Everyone is Canceled” telah memaparkan bahwa hampir semua orang pernah di-cancel dengan sebab yang beragam. Namun, ia juga mengatakan bahwa membatalkan seseorang tidak berarti akan mengubah perilaku kita atau orang tersebut.
Meski demikian, rasanya hal ini tidak berlaku di Korea Selatan yang memiliki budaya kuat dalam hal boikot selebriti. Salah satu kasus yang terkenal adalah ketika influencer terkenal dan pemain reality show Netflix ‘Single’s Inferno’, Song Ji-a, ketahuan menggunakan barang-barang desainer palsu. Masyarakat Korea Selatan merasa tertipu oleh Ji-a yang berhasil membangun citra anak orang kaya. Alhasil, Ji-a menjadi topik terhangat di seluruh media massa dan media sosial Korea yang menghujatnya setiap hari. Hingga pada akhirnya, Ji-a harus menghapus seluruh unggahan media sosialnya dan menghilang dari industri hiburan Korea Selatan selama beberapa saat.
Source: Change.org
Di Indonesia, cancel culture masih menjadi fenomena yang asing. Mungkin tidak asing untuk dikenal, tapi sulit untuk diimplementasikan. Salah satu contohnya adalah ketika Saipul Jamil terjerat kasus pelecehan seksual dan di penjara. Masyarakat beramai-ramai memboikot penampilan Saipul Jamil di televisi karena dianggap dapat melukai keluarga korban. Namun, ketika dibebaskan, Saipul Jamil malah disambut meriah dan tetap muncul di televisi.
Hal ini kemudian sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh Anjarini (2020), dimana cancel culture di Indonesia nyatanya masih sebatas pengajuan petisi daring dan tidak banyak memberikan efek jera pada tokoh publik, justru melanggengkan masyarakat untuk mengunggah komentar penghinaan pada tokoh tersebut.
Pemboikotan pada brand juga kerap kali terjadi di Indonesia. Saat ini, dalam rangka mendukung pembebasan Palestina, beberapa masyarakat memboikot Starbucks, Pizza Hut, dan beberapa brand lain yang kabarnya mendukung atau disokong oleh Israel. Meski demikian, tampaknya hal-hal ini lebih banyak terjadi di kota-kota besar, sedangkan di kota-kota yang lebih kecil, restoran-restoran tersebut masih ramai pengunjung.
Cancel culture, seperti pedang bermata dua, dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial ketika diterapkan dengan tepat di media sosial, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tokoh publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran tentang keadilan. Di sisi lain, cancel culture terkadang dapat menjadi ancaman di lanskap digital. Implementasi yang kurang didasarkan pada nilai moral dan kebijaksanaan mungkin akan menggambarkan masyarakat sebagai tak tercela dan memberi mereka otoritas untuk mencemooh orang lain. Hal ini kemudian dapat mengarah pada manipulasi opini publik.
Lalu, sebagai praktisi PR, apa yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan cancel culture?
Dalam iklim cancel culture, individu dapat dengan cepat mengeluarkan kritik dan juga menarik diri. Sebagai praktisi PR yang mewakili seorang tokoh atau brand yang terkena cancel, maka kita harus menyambut perbedaan nilai dan pendapat dengan kesempatan untuk dialog terbuka. Schneider (2019) dalam studinya memperkenalkan C.H.I.C, yaitu context (konteks), history (sejarah), intention (tujuan), dan criticism (kritik). Ia mengatakan bahwa di situasi di mana pernyataan akan dibuat atau sebuah tindakan akan dilakukan dan dipertontonkan serta diterima oleh publik, maka empat aspek di atas perlu diperhatikan.
Ia melanjutkan bahwa selain mengakui perilaku yang merugikan dan menciptakan ruang di mana percakapan konstruktif dapat terjadi, upaya membangun kembali reputasi dan kepercayaan publik juga bergantung pada bagaimana tokoh atau brand tersebut melakukan rekonsiliasi. Dengan mengakui kesalahan secara terbuka, meminta maaf dengan tulus ketika diperlukan, dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah, dapat menjadi beberapa cara untuk mencapai rekonsiliasi.
Bagaimana dengan brand? Sebagai praktisi PR, hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan brand tersebut dengan konsumen dan pemangku kepentingan lain. Setelah mengidentifikasi risiko, tindakan tanggap darurat untuk menenangkan situasi perlu dilakukan, seperti memberikan klarifikasi atau permintaan maaf langsung kepada pihak yang terpengaruh. Yang terpenting adalah stay open and transparent. Lalu, media sosial dan media massa dapat digunakan untuk menyebarkan narasi positif tentang brand dan menyoroti kontribusi lainnya.
Pada akhirnya, budaya boikot massal ini pasti tetap akan terjadi di Indonesia, pada tokoh publik atau mungkin pada brand. Sebagai praktisi PR, penting untuk menilai situasi dan identifikasi masalah dini serta menggunakan strategi yang responsif dan adaptif. Dengan demikian, rekonsiliasi dapat tercapai sehingga keadaan dapat kembali pulih di mata publik.
Referensi:
Altamira, Melisa Bunga and Movementi, Satwika Gemala (2023) "Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur," Jurnal Vokasi Indonesia: Vol. 10: No. 1, Article 5. https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5
Anjarini, D. N. (2020). Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea. Jurnal Scientia Indonesia, 6(1), 59–82. https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36131
Bromwich, J. E. (2018, June 28). Everyone is canceled. The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/06/28/style/is-it-canceled.html
D. Clark, M. (2020). DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture”. Communication and the Public, 5(3-4), 88-92. https://doi.org/10.1177/2057047320961562
Schneider, Z. M. (2019). Tools for Navigating Public Relations in a “Cancel Culture” Climate. https://remix.berklee.edu/graduate-studies-global-entertainment-business/217/